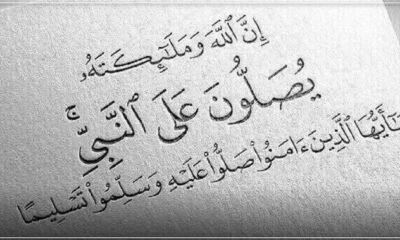Menulis Cerpen
Rindu di Balik Serambi Pesantren

Fajar menatap senja dari jendela kamarnya. Cahaya oranye kemerahan menembus tirai tipis, menari di dinding asrama. Senja itu mengingatkannya pada rumah—aroma teh hangat yang disiapkan ibu, tawa ayah di teras, bisik lembut malam yang selalu menenangkan hatinya. Kini, semua itu hanya ada dalam ingatan, menimbulkan gejolak rindu yang menggebu.
Sejak seminggu lalu, ia harus tinggal di pesantren. Dunia barunya keras, penuh disiplin, jauh dari tangan hangat ibu dan suara ayah yang menenangkan. Rindu menekan dadanya seperti batu yang tak tampak, membuat napasnya berat di setiap subuh yang sunyi. Saat azan berkumandang, Fajar tetap berharap tangan ibu ada di bahunya, membangunkannya dengan senyum.
Di ruang makan, ia menuang nasi sendiri. Suara sendok beradu mangkuk terdengar asing. Teman-teman santrinya makan dengan tenang, tapi Fajar merasa seperti berjalan sendirian di lorong panjang sunyi. “Aku bisa kuat,” gumamnya, tapi hatinya berontak. Rindu itu menjeratnya. Ia ingin menangis, ingin memeluk ibu, ingin mendengar tawa ayah.
Sore itu, saat piket, Fajar menatap kamar lain yang rapi. Tangannya gemetar saat menyapu lantai. Setiap gerakan terasa lambat, berat, karena rindu dan rasa bersalah karena terbiasa dimanja bercampur menjadi satu. Ia menahan air mata di balik tirai kamar mandi, takut ada yang melihat.
Antara rindu dan logika
Malamnya, duduk di serambi pesantren, ia membuka buku catatan. Pena menari di atas kertas:
“Ibu, Ayah… aku rindu. Semoga kalian sehat dan bahagia di rumah. Aku berusaha kuat di sini. Tolong doakan aku selalu.”
Kenangan masa kecil muncul, seperti ombak yang datang tanpa diundang. Fajar teringat ayah yang mengajarinya naik sepeda, ibu yang menunggunya pulang sekolah dengan senyum hangat. Setiap detik kenangan itu membuat rindunya semakin menyesakkan.
Hari-hari berlalu. Shalat, belajar, piket, tidur, doa. Fajar mulai memahami bahwa pesantren bukan hanya soal disiplin, tapi soal belajar menahan rindu, belajar mandiri, dan menerima kenyamanan yang dulu ia anggap biasa. Ia belajar menyiapkan makan, merapikan kamar, bahkan menahan keinginan untuk menelepon orang tua setiap hari.
Suatu sore, Fajar duduk di bawah pohon beringin tua di halaman pesantren. Angin berbisik melalui daun-daun, membawa aroma tanah basah. Ponselnya bergetar. Pesan dari ayah:
“Nak, ibu dan ayah merindukanmu. Kita semua berdoa untukmu. Semoga kau tetap kuat dan sabar.”
Fajar tersenyum tipis. Matanya berkaca-kaca. Ia membalas dengan satu kata di hatinya: “Amin.” Malam itu, di serambi, ia menatap langit berbintang. Ia sadar, jarak fisik tak mampu memisahkan doa dan cinta.
Rindu bertranformasi
Beberapa hari kemudian, Fajar mulai menemukan kekuatan baru. Ia menata meja makan sendiri, membantu teman yang kesulitan, menghadapi setiap tugas dengan ketenangan. Rindu yang dulu terasa menyiksa kini berubah menjadi dorongan untuk menjadi lebih dewasa, lebih sabar.
Saat akhir minggu tiba, orang tuanya datang menjemput. Fajar berlari memeluk mereka erat. Ibu menangis, ayah tersenyum hangat. “Nak, lihat… kau sudah tumbuh kuat,” kata ibu.
Di serambi pesantren, Fajar menatap senja sekali lagi. Ia berbisik pada dirinya sendiri:
“Rindu ini mengajarkanku, bahwa cinta orang tua tak selalu hadir dalam pelukan. Kadang, cinta itu ada dalam doa yang menghubungkan hati, dalam ketekunan, dalam keberanian untuk mandiri. Rindu bukan beban, tapi guru yang menguatkan jiwa.”
Dan ia tahu, setiap rindu yang ia rasakan adalah pengingat, “kasih sayang, kesabaran, dan tanggung jawab adalah warisan terbesar orang tua, dan menahan rindu adalah bentuk cinta yang tak kalah kuat dari pelukan.“
penulis: anugrah24